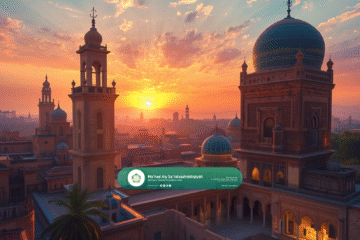saidusshiddiqiyah.ac.id— Penaklukan Yerusalem (al-Quds) oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 638 M merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah dunia Islam. Peristiwa ini tidak hanya penting karena posisi Yerusalem sebagai kota suci bagi tiga agama Abrahamik, tetapi juga karena cara penaklukannya yang berbeda dari praktik perang pada masa kuno, yakni tanpa pembantaian, tanpa penjarahan, dan disertai piagam perlindungan terhadap pemeluk agama lain yang kemudian dikenal sebagai Al-‘Uhda al-‘Umariyya. Bagi dunia Islam, peristiwa ini bukan sekadar kemenangan militer, melainkan juga manifestasi nilai keadilan sosial dan moralitas Islam.
Banyak sejarawan Barat maupun Muslim menilai peristiwa ini sebagai paradigma baru dalam hubungan antaragama. Karen Armstrong menyebutnya sebagai “a model of mercy in a violent age”, sementara Thomas Arnold menganggap perjanjian Umar sebagai “one of the most remarkable documents in the history of religious tolerance”.
Dalam tulisan ini, penulis akan menyajikan narasi lengkap yang mencakup kondisi geopolitik, kisah perjalanan Umar, detail perjanjian, serta dampak sosial-keagamaan jangka panjangnya, disertai sumber rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kelemahan Bizantium Setelah Perang Berkepanjangan
Awal abad ke-7 merupakan masa krisis besar bagi Kekaisaran Bizantium. Setelah terlibat dalam perang panjang selama 26 tahun (602–628 M) melawan Persia Sasaniyah, kekaisaran yang berpusat di Konstantinopel tersebut mengalami kehancuran ekonomi dan kemunduran militer. Wilayah-wilayah timur, seperti Suriah, Palestina, dan Mesopotamia, menjadi sangat rapuh secara politik.
Walter Kaegi (1992) mencatat bahwa setelah perang tersebut, Bizantium “was unable to replenish its shattered armies”, dan sistem administrasi fiskalnya mengalami kelumpuhan. Wabah penyakit, kematian massal, serta hilangnya tenaga produktif semakin mempercepat kehancuran sosial. Dalam situasi inilah pasukan Muslim datang membawa stabilitas baru melalui struktur pemerintahan yang lebih efisien, kepemimpinan moral, serta visi politik yang berlandaskan keadilan.
Ekspansi Islam di Syam
Ekspansi Islam di Syam tidak terjadi secara tiba-tiba. Pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq (632–634 M), ekspansi ini dimulai sebagai upaya melindungi perbatasan utara Jazirah Arab dari ancaman Bizantium. Pasukan Muslim terdiri atas beberapa detasemen yang berada di bawah komando Khalid bin al-Walid, Amr bin al-Ash, Yazid bin Abi Sufyan, dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah.
Fred M. Donner (1981) menegaskan bahwa ekspansi ini tidak semata-mata didorong oleh motif militer atau ekonomi, melainkan juga oleh visi moral dan keagamaan untuk membangun tatanan sosial baru yang lebih adil. Setelah Damaskus jatuh pada tahun 635 M, perhatian kemudian beralih ke Yerusalem sebagai benteng terakhir Bizantium di wilayah selatan Syam.
Pertempuran Yarmuk dan Jatuhnya Dominasi Bizantium
Pertempuran Yarmuk (636 M) menjadi titik balik penting dalam sejarah. Dalam pertempuran besar ini, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid berhasil mengalahkan kekuatan Bizantium yang jumlahnya jauh lebih besar. Hugh Kennedy (2007) menggambarkan Yarmuk sebagai “one of the most decisive battles in world history” karena pertempuran ini menentukan nasib seluruh kawasan Levant.
Kemenangan di Yarmuk menghancurkan struktur militer Bizantium dan membuka jalan bagi penaklukan Yerusalem secara damai dua tahun kemudian. Tidak seperti penaklukan Romawi atau Persia sebelumnya, ekspansi Islam ditandai oleh disiplin pasukan, larangan terhadap perusakan tempat ibadah, serta kebijakan toleransi terhadap penduduk lokal.
Perjalanan Umar ke Yerusalem: Simbol Kepemimpinan dan Kesederhanaan
Yerusalem dikepung oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Meskipun pengepungan berlangsung selama beberapa bulan, tidak terjadi pertumpahan darah besar. Abu Ubaidah dikenal sebagai sosok yang lembut dan sangat religius, sehingga pengepungan dilakukan dengan penuh kehati-hatian terhadap kota yang memiliki makna suci bagi umat Islam.
Patriark Sophronius, pemimpin Gereja Ortodoks Yerusalem, akhirnya bersedia menyerahkan kota tersebut dengan satu syarat utama, yaitu penyerahan dilakukan langsung kepada Khalifah Umar bin Khattab. Moshe Gil (1997) menilai langkah ini sebagai strategi politik yang cerdas untuk memperoleh jaminan keamanan langsung dari otoritas tertinggi umat Islam.
Mendengar permintaan itu, Umar bin Khattab segera berangkat dari Madinah menuju Yerusalem. Kisah perjalanannya kemudian menjadi simbol keadilan dan kesederhanaan kepemimpinan Islam. Menurut al-Baladzuri dan Ibn Sa‘d, Umar hanya ditemani seorang pelayan dan seekor unta yang mereka tunggangi secara bergantian.
Ketika memasuki Yerusalem, Umar disambut oleh Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan Khalid bin al-Walid. Melihat pakaian Umar yang sangat sederhana dan berlumur lumpur, para jenderal merasa malu. Umar lalu menegur mereka, “Kita dahulu kaum yang hina, lalu Allah memuliakan kita dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain dari Islam, niscaya kita akan kembali hina.”
Kisah ini menggambarkan moralitas Islam yang menolak kemegahan duniawi serta menegaskan pentingnya keadilan dan amanah dalam kepemimpinan. Perjalanan Umar menuju Yerusalem pun menjadi salah satu narasi paling terkenal dalam sejarah Islam.
Pertemuan Umar dan Patriark Sophronius
Pertemuan antara Umar bin Khattab dan Patriark Sophronius berlangsung dalam suasana penuh hormat dan keterbukaan. Sumber-sumber Kristen mencatat bahwa Sophronius merasa kagum terhadap kebijaksanaan Umar yang tidak memperlakukannya sebagai musuh, melainkan sebagai mitra dalam dialog spiritual.
Oleg Grabar (1996) menulis bahwa Sophronius “saw in Umar not a conqueror but a just arbiter.” Pernyataan ini menggambarkan kuatnya kesan moral yang ditinggalkan Umar pada pemimpin gereja tersebut, yang sebelumnya diliputi kekhawatiran akan terjadinya kekerasan dan penjarahan sebagaimana lazim dalam peperangan.
Perjanjian Umar (Al-‘Uhda al-‘Umariyya): Manifesto Toleransi
Perjanjian Umar merupakan salah satu dokumen terpenting dalam sejarah hukum Islam dan hubungan antaragama. Naskah perjanjian ini tercatat dalam Futuh al-Buldan karya al-Baladzuri, Tarikh al-Tabari, serta sejumlah sumber Kristen abad pertengahan, seperti Chronicon Paschale. Pokok-pokok isi perjanjian tersebut meliputi:
- Perlindungan atas jiwa dan harta seluruh penduduk Yerusalem, termasuk pemuka agama, perempuan, dan anak-anak.
- Jaminan kebebasan beragama serta larangan keras memaksa siapa pun untuk memeluk Islam.
- Perlindungan terhadap tempat ibadah Kristen, yaitu tidak boleh dirusak, dirampas, maupun dialihfungsikan menjadi masjid.
- Pemberian izin kepada kaum Yahudi untuk kembali bermukim di Yerusalem setelah sebelumnya dilarang oleh pihak Bizantium.
Milka Levy-Rubin (2011) menyebut perjanjian ini sebagai “blueprint of tolerance” dalam sistem hukum Islam awal. Selama berabad-abad, Covenant of Umar dijadikan model dalam perlakuan terhadap non-Muslim (ahl al-dzimmah) di berbagai wilayah kekhalifahan. Thomas Arnold bahkan menyebutnya sebagai “The Magna Carta of religious tolerance.”
Umar dan Gereja Makam Kudus: Teladan Etika Lintas Iman
Kisah penolakan Umar bin Khattab untuk menunaikan salat di dalam Gereja Makam Kudus menjadi simbol luhur etika Islam dalam menghormati tempat ibadah agama lain. Ketika Sophronius mempersilakan Umar untuk salat di dalam gereja, Umar menolaknya karena khawatir generasi Muslim setelahnya akan menuntut kepemilikan gereja tersebut. Ia kemudian melaksanakan salat di luar bangunan gereja, dan di lokasi itulah kelak didirikan Masjid Umar.
Tindakan ini menjadi preseden penting dalam fikih Islam terkait penghormatan terhadap hak-hak keagamaan non-Muslim, sekaligus mencerminkan pandangan jauh ke depan Umar dalam mencegah potensi konflik sektarian.
Pembersihan Area Haram al-Sharif dan Pembentukan Lanskap Islam di Yerusalem
Umar bin Khattab kemudian mengunjungi area Haram al-Sharif (Temple Mount) yang pada masa itu dipenuhi puing dan reruntuhan peninggalan Romawi. Ia memimpin langsung pembersihan kawasan tersebut, bahkan memungut puing-puing dengan tangannya sendiri.
Di atas lahan itu kelak dibangun dua monumen besar Islam, yaitu:
• Masjid al-Aqsa, yang penyelesaiannya berlangsung pada masa Khalifah Abdul Malik dan al-Walid (abad ke-7–8 M).
• Dome of the Rock (Qubbat al-Sakhra), yang kemudian menjadi simbol kemegahan spiritual Islam di Yerusalem.
Menurut Oleg Grabar (1996) dan K.A.C. Creswell (1958), tindakan Umar ini menjadi fondasi bagi terbentuknya tata ruang keagamaan Islam di Yerusalem, yang berkembang berdampingan secara harmonis dengan situs-situs suci Yahudi dan Kristen.
Dampak Politik, Sosial, dan Keagamaan Jangka Panjang
1. Dampak Politik
Penaklukan Yerusalem memperkuat kontrol kekhalifahan atas wilayah Syam dan Palestina. Hugh Kennedy (2007) menilai Yerusalem sebagai “a symbolic capital of Islam’s universal vision.” Setelah peristiwa ini, kekuasaan Bizantium di kawasan Levant tidak pernah pulih sepenuhnya.
2. Dampak Sosial
Umar bin Khattab mengatur tata kelola masyarakat multireligius melalui sistem ahl al-dzimmah. Moshe Gil (1997) mencatat bahwa komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara relatif damai hingga masa Perang Salib.
Sebaliknya, ketika Tentara Salib merebut Yerusalem pada tahun 1099 M, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap penduduk kota. Kontras ini semakin menegaskan keunikan penaklukan Umar sebagai model kemanusiaan dalam sejarah peperangan.
3. Dampak Keagamaan
Penaklukan ini menegaskan Yerusalem sebagai kota suci ketiga dalam Islam setelah Makkah dan Madinah. Kota ini kemudian berkembang menjadi pusat studi keagamaan, spiritualitas, dan interaksi lintas iman. K.A.C. Creswell menegaskan bahwa berkat perlindungan Umar, situs-situs suci di Yerusalem dapat tetap terjaga hingga kini.
Analisis Nilai dan Relevansi Historis
Penaklukan Yerusalem menampilkan paradigma politik Islam yang humanis, yaitu bahwa penaklukan tidak dimaknai sebagai dominasi total, melainkan sebagai upaya membangun tatanan sosial baru yang berlandaskan keadilan. Dalam konteks kontemporer, Al-‘Uhda al-‘Umariyya tetap relevan sebagai model pengelolaan keberagaman dan penguatan dialog antaragama.
Kepemimpinan Umar bin Khattab menunjukkan bahwa legitimasi politik dalam Islam tidak bersumber dari kekerasan, melainkan dari moralitas, keadilan, serta pengabdian terhadap kemanusiaan.
Dari kisah di atas dapat disimpulkan bahwa penaklukan Yerusalem oleh Umar bin Khattab pada tahun 638 M bukan hanya merupakan kemenangan militer, melainkan juga kemenangan moral dan kemanusiaan. Pada masa yang sarat dengan kekerasan, Umar menghadirkan model pemerintahan yang menegakkan keadilan, menghormati perbedaan, serta menjamin kebebasan beragama.
Perjanjian Umar menjadi warisan universal yang menegaskan bahwa kekuasaan sejati lahir dari keadilan dan kasih sayang. Dalam konteks global modern, prinsip-prinsip yang dirintis Umar tetap relevan dan terus menginspirasi pengembangan tata kelola masyarakat multikultural yang damai dan inklusif.
Referensi
Kennedy, Hugh. 2007. The Great Arab Conquests. Terj. Ratih Ramelan. Sunt. Ade Fakih Kurniawan. Tangerang: PT Pustaka Alvabet Anggota IKAPI.
Suntiah, Ratu, dan Maslani. 2017. Sejarah Peradaban Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Aizid, Rizem. 2024. Sejarah Lengkap Yerussalem Pergulatan Panjang Agama dan Politik Sejak Era Klasik Sampai Mutakhir. Yogyakarta: DIVA Press.
Khalid, Mustafa. 2017. The Greatest Story Of Muhammad Biografi Nabi Muhammad SAW dan Kisah Inspiratif Para Sahabat Nabi. Yogyakarta: Ide Segar Media.
Gunadi, RA dan Mohammad Shoelhi. 2002. Dari Penaklukan Jerusalem Hingga Angka Nol. Jakarta: Republika.
Putra, R.D.A. (2023). Penaklukan Yerusalem (Pertempuran Shalahuddin Al-Ayyubi Dengan Richard I Dalam Perang Salib Iii 1189-1192 M). (Doctoral Dissertation). IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.
Pratama, M.A.Q. 2018. “Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab”. JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), Vol. 2, No. 1.
Ritonga, A.S., A.R. Tanjung, dkk. 2025. “Model Kepemimpinan Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab. Elbayyinah: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 2.
Ikrom, M., M.H. Maulana, dkk. 2024. “Peradaban Islam di Masa Khulafaurrasyiddin”. Journal of Religion and Social Community, Vol. 1, No. 2.
Kontributor: Arman Juliansyah, Semester III
Editor: Winda K.N