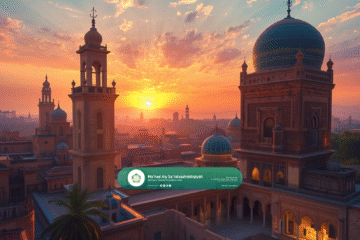saidusshiddiqiyah.ac.id— Pascakemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, pusat pemerintahan di Jakarta dilanda berbagai kekacauan akibat para penjajah yang enggan mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun Jepang telah mengetahui adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, mereka tetap bersikukuh bahwa kekuasaan dan tanggung jawab keamanan masih berada di tangan mereka sampai Sekutu, khususnya Inggris, datang.
Di sisi lain, Inggris sebagai bagian dari Sekutu lebih memfokuskan diri pada repatriasi tawanan perang tanpa memedulikan kedaulatan negara baru. Kondisi ini menjadikan Jakarta tidak lagi layak sebagai pusat pemerintahan.
Situasi tersebut semakin diperparah oleh tekanan dari NICA (Netherlands Indies Civil Administration) serta potensi penangkapan para pemimpin Republik. Operasi intelijen dan aktivitas militer Belanda menambah risiko terhadap kelangsungan pemerintahan Indonesia. Selain itu, banyak negara pada masa itu belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda melalui NICA menganggap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai tindakan ilegal dan berupaya mengambil alih kembali kekuasaan.
Akibatnya, pada kurun waktu 1945-1949, Indonesia dihadapkan pada perjuangan berat di bidang diplomasi dan militer untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaannya sah dan berdaulat.
Pada 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan dan digantikan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai langkah awal pembentukan struktur pemerintahan yang lebih resmi. Namun, situasi Jakarta semakin memanas akibat aktivitas intelijen dan gerakan kontra dari pihak Belanda.
Tidak lama kemudian, Yogyakarta, sebuah kota dengan kondisi politik yang relatif lebih stabil serta dukungan penuh dari Kesultanan yang menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada saat yang sama, Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang menegaskan bahwa Yogyakarta resmi bergabung dan mengakui Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang sah serta menyatakan dukungan penuh terhadapnya.
Dukungan tersebut menjadi sumber harapan bagi Indonesia yang saat itu tengah mengalami krisis keamanan dan legitimasi politik. Dalam kondisi tersebut, pemerintah juga mulai mencari lokasi yang lebih aman untuk menjalankan roda pemerintahan. Pada Oktober 1945, terjadi berbagai insiden bentrokan antara pejuang Indonesia dan NICA di Jakarta, terutama di wilayah Jatinegara dan Gambir. Para pejabat Republik Indonesia pun mulai mendapat pengawasan ketat karena keselamatan mereka terancam oleh aktivitas NICA.
Pada November 1945, Pemerintah Republik Indonesia mulai membahas rencana pemindahan pusat pemerintahan. Melalui rapat kabinet, beberapa daerah dipertimbangkan sebagai calon lokasi ibu kota, di antaranya Solo, Yogyakarta, Madiun, dan Magelang. Di antara pilihan tersebut, Yogyakarta dinilai paling unggul karena kondisi politiknya relatif stabil dan kepemimpinannya kredibel. Sementara itu, kota-kota lain seperti Solo dan Madiun masih rawan konflik internal serta memiliki basis kelompok kiri yang cukup kuat.
Memasuki Desember 1945, tekanan militer Sekutu semakin brutal. NICA semakin terang-terangan berupaya menangkap para pemimpin Republik Indonesia. Situasi ini membuat ruang gerak pemerintah semakin terbatas dan tidak lagi leluasa beraktivitas di Jakarta.
Dalam kondisi genting tersebut, Sultan Hamengkubuwono IX tampil sebagai tokoh kunci yang secara aktif membantu Republik Indonesia. Ia menyediakan Gedung Agung sebagai tempat kegiatan pemerintahan, menjamin keamanan dan logistik, serta memberikan ruang bagi kementerian-kementerian untuk menjalankan tugasnya.
Pada 28 Desember 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan rapat final dan secara resmi memutuskan bahwa pusat pemerintahan harus dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi keamanan yang tidak lagi dapat dijamin. Pada 2–3 Januari 1946, pemerintah melakukan persiapan keberangkatan secara diam-diam. Langkah ini diambil agar kabar pemindahan pusat pemerintahan tidak bocor kepada pihak Belanda, mengingat adanya kekhawatiran bahwa mereka akan menangkap para pemimpin negara dalam perjalanan.
Pada 4 Januari 1946, terjadilah puncak peristiwa pemindahan pusat pemerintahan. Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berangkat bersama para menteri pada dini hari dari Jakarta dan tiba di Yogyakarta tanpa mengalami insiden. Keputusan ini terbukti sangat tepat karena membawa Republik Indonesia keluar dari ancaman langsung terhadap keselamatan pemerintahan.
Rombongan pemerintah disambut langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII, serta diterima dengan hangat oleh masyarakat Yogyakarta. Gedung Agung kemudian resmi difungsikan sebagai Istana Kepresidenan, dan Yogyakarta pun menjadi ibu kota de facto Republik Indonesia.
Pemindahan ini tidak hanya menyelamatkan struktur pemerintahan Republik Indonesia, tetapi juga memperkuat legitimasi Yogyakarta sebagai pusat perlawanan politik dan diplomasi dalam Sejak Januari hingga Desember 1946, Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan penuh, dan seluruh aktivitas kenegaraan dipindahkan ke kota tersebut. Berbagai institusi negara, mulai dari departemen-departemen, perwakilan diplomatik, pusat strategi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), kantor-kantor kabinet, hingga percetakan uang Oeang Republik Indonesia (ORI), resmi beroperasi di Yogyakarta. Pada periode ini, Yogyakarta benar-benar berperan sebagai pusat kendali negara pada masa yang paling krusial.
Agresi Militer Belanda I yang terjadi pada Juli 1947 dihadapi dengan tetap bertahannya pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Upaya Belanda untuk menghancurkan kedaulatan Indonesia pun gagal. Namun, pada Agresi Militer Belanda II, Desember 1948, Belanda berhasil memasuki Yogyakarta melalui Operatie Kraai. Pasukan Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) bersama pasukan payung Belanda menerobos kota dan menggeledah pusat-pusat pemerintahan untuk mencari pimpinan Republik Indonesia.
Sejumlah tokoh penting, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Haji Agus Salim, serta beberapa tokoh lainnya, ditawan tanpa perlawanan. Hal ini bukan karena mereka menyerah, melainkan karena mereka sengaja tetap berada di kota agar Republik Indonesia tidak tampak melarikan diri dari tanggung jawab politik dan perjuangan.
Soekarno dan Mohammad Hatta kemudian diasingkan ke Bangka, meskipun ditempatkan di lokasi yang berbeda. Belanda mengira bahwa dengan menawan presiden dan wakil presiden, Republik Indonesia akan runtuh. Namun, anggapan tersebut keliru. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) justru berdiri di Sumatra dan melanjutkan roda pemerintahan.
Serangan Umum 1 Maret 1949 dilancarkan dan mengguncang posisi Belanda, baik secara militer maupun politik. Tekanan internasional terhadap Belanda pun semakin menguat. Peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahwa Republik Indonesia tetap hidup dan berdaulat meskipun para pemimpinnya berada dalam penahanan.
Puncak perjuangan tersebut terjadi pada 27 Desember 1949, ketika kedaulatan Indonesia akhirnya diakui secara resmi. Setelah pengakuan kedaulatan itu, ibu kota negara kembali dipindahkan ke Jakarta.
Referensi :
Kahin, George McT. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
Ricklefs, M.C. 2008. A History of Modern Indonesia Since c. 1200. Stanford: Stanford University Press.
Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto. 1984. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.
Suryomihardjo, A. 1985. Yogyakarta: Sejarah dan Perkembangannya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Arsip Nasional Republik Indonesia. 1945-1949. Dokumen Pemerintahan. Jakarta: ANRI.
Shiraishi, Takashi. 1990. An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–1926. Ithaca: Cornell University Press.
Legge, J.D. 1964. Indonesia. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Kontributor: Ahmad Baehaqi Thohari, Semester V
Editor: Winda K.N